Saya tidak pernah membayangkan diri ini berada di jalur pendakian Gunung Ciremai. Sama sekali. Bagi saya, Gunung Ciremai sama seperti Gunung Kerinci. Menyeramkan. Bukan karena hantu atau penampakan di gunung.
Nyatanya, Mei 2018 saya mendapati diri saya tengah mendaki Gunung Ciremai. Dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, saya meluncur ke Majalengka dengan menggunakan bus. Semua perbekalan siap sudah. Hal yang membuat saya semakin antusias sekaligus deg-degan adalah: saya melakukan pendakian ini sendirian. Solo hiking.
Hobi untuk berkelana secara independen ini sebenarnya sudah cukup lama saya mulai. Perjalanan seorang diri ke Yogyakarta sekitar tahun 2009 menjadi seperti candu. Saya mencobanya sekali, lalu ketagihan.
Semakin lama, gaya berlibur semacam ini jadi terasa kian menyenangkan. Bahkan saya menyebutnya menjadi kebutuhan. Kebutuhan untuk kabur dari orang-orang.
Awalnya, saya hanya berani untuk liburan sendirian ke tempat yang saya anggap ramah wisatawan: kota yang menyediakan transportasi dan akomodasi dengan mudah. Kemudian saya mencoba menjelajahi pantai-pantai sepi di beberapa kabupaten atau kota kecil.
Akhirnya saya mencoba untuk membawa gaya berlibur ini ke jalur pendakian. Saya pun melakukan test drive di Gunung Lembu dan Gunung Bongkok di Purwakarta. Keduanya tidak dikategorikan sebagai gunung, mungkin. Namun, percayalah, apalah arti sebuah nama. Medan pendakian keduanya ternyata tidak kalah dengan medan pendakian beberapa gunung yang pernah saya daki sebelumnya: sama-sama “asoy”.
Lantas, apa yang saya dapatkan dari pendakian seorang diri? Buat saya yang tidak terlalu senang mengobrol atau mendengar orang berbicara lama-lama, hal yang paling melegakan dari pendakian seorang diri adalah ketenangan.
Solo hiking membawa ketenangan buat saya. Jeda di antara suara-suara manusia yang selalu mengajak ngobrol. Saya menyebutnya: istirahat (hampir) total dari interaksi dengan manusia.
Saya tidak mau menjadi filsuf dadakan atau berfilosofi dengan menyebut solo hiking memberi saya ruang untuk mendengar suara sendiri, merenung, berpikir, atau apa pun. Bukan, bukan saya. Jangankan untuk merenungkan hal-hal berat. Hal yang saya pikirkan tidak jauh-jauh dari kebutuhan dasar saya: makanan, air, dan istirahat.
Baca juga: Etika Pendakian, Perlukah? di sini.

Anda mungkin bertanya: apakah saya merasa kesepian di jalur pendakian? Tentu saja, terkadang. Tidak bisa dimungkiri, ada kalanya saya merasa perlu teman bicara. Namun, saya tidak benar-benar sendirian, bukan? Saya tidak sedang berada di rimba Amazon.
Hal seputar jalur pendakian atau cuaca biasanya menjadi topik perbincangan saya dengan para pendaki lain yang berpapasan. Di camp ground pun, saya menyempatkan diri menyapa dan mengobrol dengan penghuni tenda tetangga. Saya tetap bekomunikasi dengan orang lain, dengan takaran yang saya inginkan.
Hal lain yang saya rasakan ialah perbedaan kecepatan berjalan. Saya tidak mengukur secara pasti apakah pendakian sendirian benar-benar membuat saya berjalan lebih cepat (karena saya tidak pernah membandingkan waktu tempuh pendakian gunung yang sama sendirian dan bersama rombongan). Saya hanya merasa berjalan lebih cepat dari biasanya.
Ketika saya berjalan dalam kelompok pendakian, kecepatan maksimal saya adalah kecepatan terendah salah satu anggota kelompok. Saya tidak mungkin berjalan lebih cepat dari itu, alias meninggalkan teman kelompok.
Baca juga: Gunung Lawu Jalur Cetho: Cerita Pendakian Sendirian di sini.
Di Gunung Ciremai, saya bisa mengatur kecepatan berjalan semau sendiri. Ketika semangat membara, saya bisa terus berjalan bahkan melewati pos pendakian. Ketika saya memutuskan untuk rehat pun saya bisa menentukan seberapa lama saya berhenti istirahat.

Baca juga: Summit Attack, Setelah atau Sebelum Sunrise? di sini.
Hal baru yang cukup menarik adalah reaksi para pendaki lain yang saya temui di jalur pendakian atau di base camp. Sebagian besar menunjukkan antusiasme ketika mengetahui saya mendaki sendirian. Pertanyaan mereka tidak berhenti di sana dan berlanjut untuk mencari tahu alasan saya memilih mendaki sendirian. Saya dengan semangat mencoba meyakinkan mereka betapa menyenangkannya hal yang sedang saya lakukan.
Ada juga salah satu kelompok pendaki yang menawarkan saya bergabung—yang tentunya saya tolak—karena menganggap saya mendaki sendirian karena terpaksa.
Reaksi paling cihui dari pendaki yang papasan di Ciremai:
👩Sendirian bgt, A?
👨Iya
👩Jomblo ya hehehe
👨Istri baru meninggal
👩Oh… Inalillahi…
🐞: krik krik
👨: Sy lanjut jalan— Iyos Kusuma (@iyoskusuma) May 12, 2018
Apa saya merasa takut di perjalanan? Iya. Mendaki sendirian berarti bertanggung jawab secara penuh untuk keselamatan diri sendiri. Untuk itu, saya mempersiapkan setiap hal secara detail, seperti informasi dan perbekalan.
Pernah waktu itu, saya tergesa-gesa turun gunung karena akan hujan, hingga akhirnya kaki saya cedera. Tidak ada yang bisa membantu. Akhirnya, saya harus mengurangi kecepatan berjalan dengan kaki yang sakit.
Beberapa kali pula saya takut memilih jalan ketika menemui persimpangan di jalur pendakian. Takut salah jalan, walau saya merasa kedua jalurnya akan berpotongan di titik yang sama juga di depan. Namun, entah, tetap saya merasa takut tanpa alasan kuat.
Baca juga: Pendakian Merapi dari Selo di sini.
Satu pertanyaan yang sering ditanyakan pada saya adalah, “Yos, pernah lihat yang aneh-aneh ngga selama di gunung? Digangguin gitu?”. Jawaban saya, tidak. Saya tidak percaya dan mengakui keberadaan hantu. Jadi, jika pun ada satu hal ‘aneh’ yang terjadi, saya akan selalu berusaha mencari alasan logis sebagai penyebabnya, misalnya gravitasi atau halusinasi karena terlalu letih mendaki.
Justru saya jauh lebih takut dengan binatang buas yang bisa saya temui di perjalanan atau menemui saya di tempat kemah, misalnya babi hutan atau macan. Kalau babi kecap, saya suka. Hal lain yang juga sering saya takutkan adalah kriminalitas. Katakanlah, ada seorang yang mencari tumbal jantung manusia untuk pesugihan. Imajinasi yang cukup liar namun masuk akal.
Saya pikir itu saja hal-hal yang saya rasakan dan alami ketika saya mendaki gunung sendirian. Sisanya, tidak jauh berbeda dari pengalaman pendakian berkelompok. Beban barang pendakian pun tidak jauh berbeda, karena biasanya saya pula yang membawa beban pendakian paling banyak ketika mendaki berkelompok.
Bagaimana dengan Anda? Punyakah pengalaman menarik soal solo hiking? Atau jika belum pernah mencoba, apakah tertarik untuk mencoba sendirian di jalur pendakian?

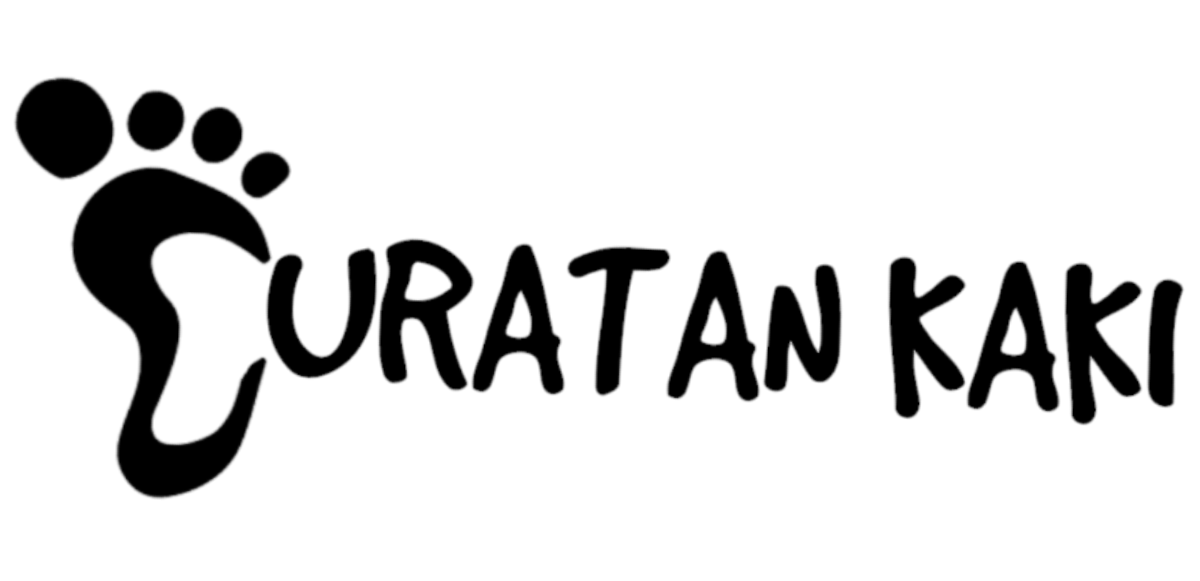

Setuju Mas Iyos, saya juga merasakan hal yang sama, enak sendiri, walau tetep ada enggak enaknya, ahahha.
Pengalaman pertama mendaki sendirian saat di G Sinabung 2012, ini naik hingga puncak gak ketemu siapapun, turun baru papasan sama pendaki yang mau naik.
Lalu yang kedua di G Muria 2015, ini pas naik papasan sama ratusan pendaki turun yang harus saya senyumin satu persatu, dan mendapat pertanyaan yang selalu berulang.
Alasan solo hiking saya sederhana, ingin fleksibel saja untuk masalah waktu dan tenaga. Selain pendakian, saya juga sering solo trekking di beberapa tempat macam air terjun atau wana wisata yang memang asyik untuk berjalan sendiri sembari mengambil foto. Terlebih sudah mulai upgrade beberapa peralatan ke ultralight. 🙂
Mungkin Mas Iyos perlu bawa GPS deh, kan sudah banyak tuh yang upload rute pendakian dalam format *.gpx, jadi akan sangat membantu untuk meyakinkan diri mengambil arah di persimpangan. Satu pasang batre alkaline cukup hingga 8-10 jam operasional.
LikeLiked by 2 people
Bener juga, saran GPS-nya saya coba pertimbangkan. Pasti berguna. Ada GPS yang direkomendasiin mungkin, Mas?
Nah, sama sekali ngga papasan sama pendaki itu yang kadang bikin ga tenang, Mas. Hahaha. Sedikit lega kalau nemu jejak sepatu. Entahlah, kadang yakin ga nyasar, tapi tetep ada rasa khawatir. Kemarin itu pas muncak ke CIremai, beberapa kali denger suara pendaki lain puluhan meter dari sebelah kanan jalur pendakian (bukan dari depan). Ini bikin ragu banget hahaha.
Untuk ultralight, saya belum sepenuhnya berani nih, Mas. Masih bawa tenda 1P, walau udah upgrade ke yang 1,5 kg (masuk kategori ultralight tent kah?). Pernah nulis soal ultralight ngga, Mas?
LikeLike
Saya kalau di lapangan biasanya pakai garmin 60csx, jadul sih, tapi bentuknya kecil dan sudah ada slot micro sd. Digantung pake carabiner kelihatan kayak hape jadul juga, ahahaha.
Mungkin perlu ditambahi kompas analog buat mempermudah membaca arah angin.
Masih bentuk draft, belum kesentuh lagi, wkwkw.
Saya sih gak paham, adakah aturan baku untuk bobot yang masuk ultralight, namun setahu saya banyak kok Mas tenda 1P yang dibawah 1kg. Contohnya seri tenda yang frameless, jadi cara mendirikanya kita wajib pakai treking pole dan tali pancang yang kuat. Tapi tenda ginian gak bisa berdiri macam medan di Pasar Bubrah, Merapi.
Bagi yang biasa mikul tenda 4-5 kg, 1.5 kg itu udah sangat melegakan Mas 🙂
LikeLike
Nah itu… Kalau urusan tempat berlindung, saya masih harus bergantung sama tenda yang “beneran tenda” nih, Mas. Untuk yang frameless, tarp tent, hammock tent, dan sebagainya ngga berani.
Siap, Mas. Saya pelajari soal GPS ini. Makasih 😃👍
LikeLiked by 1 person
saelah kasep pisan modelnaaa… hahahhaa
LikeLiked by 1 person
ah, kakak… sini aku traktir horlics :))
LikeLike