Hujan masih menghujam tenda ketika saya terbangun. Saya meraih arloji dari saku tenda lantas meliriknya. Pukul tiga dini hari.
Bukan, bukan hujan yang membangunkan saya. Tenda ini kedap air, saya tidak khawatir. Sayang, tenda ini tidak kedap suara.
Suara itu datang dari luar tenda. Saya mengintip dari celah bawah vestibule tenda. Persis di sebelah tenda saya. Padahal tadi petang masih kosong.
Para pendaki yang menghuni tenda di sebelah tenda saya terkekeh-kekeh. Ada pula lagu Despacito versi house yang diputar dari portable speaker. Pukul tiga dini hari. Di gunung. Despacito. Versi house. Gusti nu agung!
Saya berusaha tidak menggerutu apalagi menegur, tidak sudi liburan saya tercemar emosi. Sabar saja dulu. Toh tujuan saya berkemah sendirian adalah bersenang-senang.
Apa yang saya lakukan sendirian ke gunung? Istirahat total dari interaksi dengan manusia. Ya, membatasi komunikasi dengan orang lain, seminimal mungkin.
Saya bukan pemburu sunrise di puncak gunung, sebenarnya. Saya juga agak tidak nyaman kalau ada teman atau rekan yang menempel label anak gunung buat saya. Bukan. Rakata anak gunung, saya bukan.
Saya cuma suka berlibur ke tempat yang menenangkan dan berudara sejuk. Maka pilihan paling menyenangkan adalah mendaki gunung, saya pikir.

Oke, kita kembali ke dalam tenda. Malam itu, niat saya untuk melanjutkan tidur malah buyar. Rasio tidak mau diajak santai. Malah berpikir, sadarkah para tetangga ini bahwa gunung adalah tempat para pendaki mencari kesunyian, melipir sekejap dari hiruk pikuk?
Ah, tujuan orang kan berlainan. Mungkin ada yang mendaki gunung untuk ziarah, olah raga, memotret, atau gagah-gagahan.
Apa pun tujuan pendaki datang ke gunung , bukan urusan saya sebenarnya. Bebas-bebas saja selama kebebasan diri mereka tidak beririsan apalagi menyinggung kebebasan orang lain.
Namun satu hal yang menjadi rambu perilaku saya—di gunung atau bukan—adalah agar jangan sampai hal yang saya lakukan mengusik apalagi merugikan orang lain. Bersuara lantang—sekali lagi, di gunung atau bukan—bisa mengganggu orang lain. Berilah pendaki lain ruang untuk menikmati suara alam, meresapi keheningan, atau istirahat sebelum melanjutkan pendakian.

Tidak sulit rasanya mengatur volume suara kita sesuai dengan jumlah, jarak, dan daya dengar pendengar kita. Jangan, jangan salahkan suku atau daerah asal kita. Kawan saya yang berasal dari berbagai daerah bisa mengecilkan volume suara mereka ketika mereka membicarakan orang lain atau meminjam uang.
Artinya, mereka sadar akan dua hal. Pertama, suara mereka bisa terdengar orang lain. Kedua, sebenarnya mereka bisa mengatur volume suara mereka.
Baca juga: Zero Waste Adventure, Mendobrak Budaya Pendakian dengan Buku di sini.
Itu baru urusan kegaduhan. Pada hari yang sama, dan pada hari-hari pendakian sebelumnya, urusan lampu senter menjadi cerita lain.
Kerap saya merasa terganggu dengan lampu senter yang disorotkan ke tenda pada malam hari. Ketika saya sedang berada di tenda, ini mengganggu. Mau satu lapis atau dua lapis tenda saya, sorotan lampu pasti tembus.
Bahkan pada kemah terakhir, lampu senter disorotkan beberapa kali ke tenda saya. Sesekali mereka saling bertanya apakah tenda saya sedang diisi orang atau tidak, sendirian atau berduaan, seperti apa rupanya, dan seterusnya.
Entah apa tujuannya. Jika tujuan mereka memastikan saya dalam kondisi baik—karena sejak petang saya tidak muncul keluar tenda—mereka bisa menghampiri tenda dan mengucapkan permisi dan menyapa, bukan menyibak-nyibak tenda dengan sorot lampu.

Bicara soal menyapa pendaki lain, saya juga jadi ingat percakapan saya dengan seorang teman di jalur pendakian, beberapa tahun lalu.
Topik pembicaraan kami saat itu, “kalau kita ngelewatin pendaki lain yang lagi duduk istirahat di jalur pendakian, gimana kita menyapa mereka?”. Teman saya menjawab, “permisi”.
Lalu saya tanya lagi, “kenapa kita yang harus minta permisi ke orang yang duduk ngehalangin jalan? Padahal beberapa pendaki yang kita lewatin sedang istirahat di tanah yang cukup lapang, jadi seharusnya mereka bisa menepi dari jalur pendakian”.
Jawaban teman saya sederhana: kesopanan dan kesantunan. Ah, ini perkara kebiasaan dan kebebasan setiap orang memaknai “sopan”.
Baca juga: Summit Attack sebelum atau setelah Sunrise di sini.
Menurut saya, sopan itu tidak beristirahat di jalur pendakian ketika tempat pendaki rehat adalah tanah yang cukup lapang. Apalagi ketika para pendaki lain sedang ramai lalu lalang. Keadaan darurat tidak masuk dalam hitungan, oke? Akan tetapi, saya biasanya tetap sapa mereka dengan ucapan selamat siang atau selamat pagi.

Sejujurnya, saya bukan orang yang senang berkenalan atau berbasa-basi dengan orang lain. Namun, entahlah, hal ini jadi terjungkir balik ketika saya berada di gunung.
Saya selalu menyapa pendaki di jalur pendakian. Mereka yang beristirahat, mereka yang berpapasan, atau mereka yang saya persilakan untuk mendahului ketika saya ingin berjalan santai di jalur sempit.
Buat saya, menyapa pendaki lain yang saya temui di jalur pendakian atau di tempat kemah itu perlu. Pertama, senyum membuat saya senang dan melupakan letih, disadari atau tidak. Kedua, bertegur sapa dengan orang baru membuat saya merasa aman berada di alam bebas.
Maka saya anggap, etika pendakian sangat perlu untuk diindahkan oleh saya sebagai pendaki. Bagaimana menurut Anda? Seberapa penting etika pendakian menjadi rambu untuk menuntun para pendaki berperilaku di gunung?

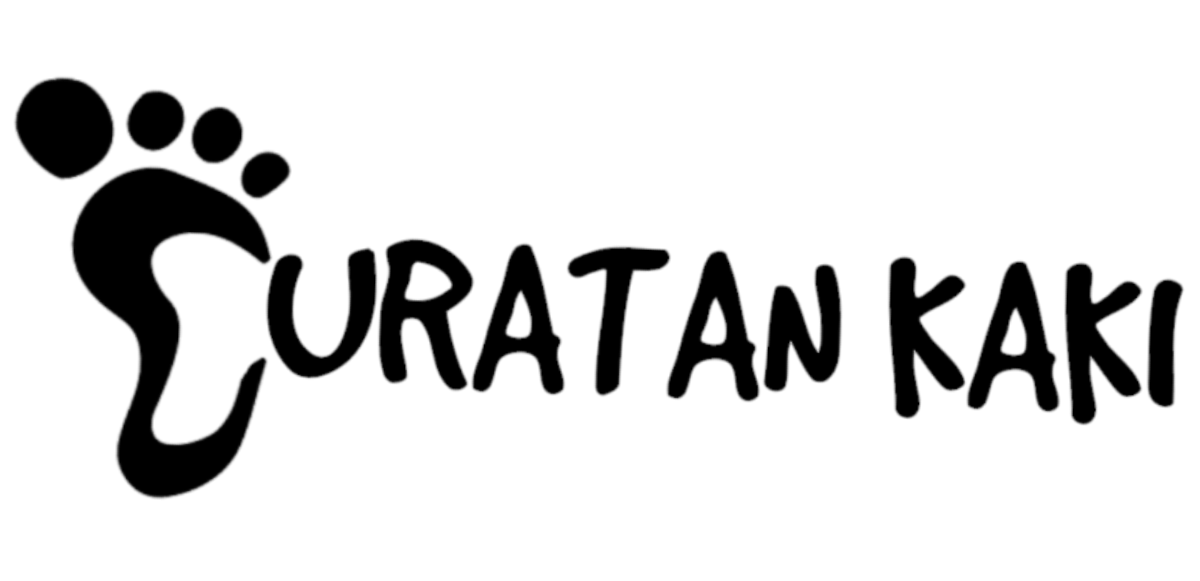

Ada perlunya juga menurutku.
Tapi aku rasa, hal-hal semacam itu menjadi cerminan perilaku mereka di rumah atau di lingkungannya juga. Orang yang terbiasa sopan, menghormati orang lain, tepo seliro, maka akan seperti itu pula dimanapun dia berada. Begitu pula sebaliknya.
Namun, memang harus ada yang dipelajari oleh mereka. Bahwa ketika kita berada di ruang publik -gunung dan alam bebas juga ruang publik, bukan?- maka seharusnya ya bertenggang rasa dengan orang lain. Tidak bisa sebebasnya. Hmmm soal menyetel musik kencang-kencang, setahuku di alam bebas pun tidak bisa sembarangan. Karena bisa mengganggu mahluk lain, baik yang terlihat maupun tidak terlihat hehehehe.
Btw, wanieueun ih kang Iyos camping di gunung sendirian? Kalau saya masih mikir-mikir 😀
LikeLiked by 1 person
Iya sih, tapi kalau di gunung (segelintir) orang kan biasanya bertingkah “aku anaknya baik banget”, yang di kota judes, di gunung ramah; yang di kota suka buang puntung rokok, di gunung jadi bawel soal sampah; dsb.. Segelintir sih, mungkin hehe..
Wuih, berani atuh (ternyata). Padahal sebelum berangkat mah mikir-mikir keneh. Hahaha.
LikeLiked by 1 person
Jadi gunung yang merubah manusia, atau sebaliknya ya? Hahahaha.
Tapi apa-apa itu memang biasanya lebih seram ketika kita bayangkan, daripada ketika kita jalani.
LikeLiked by 1 person
Hahaha saling mengubah ya.. Tapi yabg jelas aku ngga berubah, Mz…. *dilempar tenda.
Yap, selama traveling, kadang saya suka takut sama hal-hal yang sebenernya ga ada dan saya ciptain sendiri. Betul itu 😃
LikeLiked by 1 person
Semenjak zaman Instagram ini, jadi banyak yang naik gunung dadakan. Ada temanku yang bukan pendaki, tapi jadi suka mendaki karena buat dia foto-foto di puncak itu bagus banget. Nggak salah sih, hanya akan lebih baik apabila niatan mendaki itu dibarengi juga dengan belajar etika hehehe.
Tapi, kadang gak cuma di gunung sih mas. Kalau aku ke tempat sakral yang jelas-jelas untuk berdoa, masih aja ada orang-orang yang suka berisik, selfie rame-rame, dan cengegesan sendiri. Pdhl kan sudah jelas tempat itu harus hening.
LikeLiked by 1 person
Hehe, mungkin ada benernya, media sosial memicu orang lain buat datengin tempat-tempat yang keliatan bagus di Instagram orang. Mungkin sebagian di antaranya adalah mereka yang ngga peka buat ngehargain orang-orang lain yang ada di sana. Ya, ga semua.
Nah, betul itu. Ngga sopan banget ya. Jadi inget kejadian di Borobudur beberapa tahun lalu.
LikeLike
Dri yg aku dengar2 sih. Etika penting ya di pegunungann, heheh.
LikeLike