Saya mematikan head lamp yang bercokol di kepala. Napas kami mulai terasa berat. Kami mencoba mengatur ritme jalan dan napas.
Langit Rinjani mulai merona kala itu. Sinar matahari pagi perlahan menepuk lereng gunung, merayap di jalur pendakian.
Hampir pukul enam pagi. Saya bersama beberapa teman tengah mendaki di jalur puncak Gunung Rinjani.
Tiba-tiba saya teringat pemandangan yang kami lihat dari Desa Sembalun, sebelum kami memulai pendakian. Pucuk Rinjani, tempat Dewi Anjani bertahta, terlihat kemerahan dari sana.
Dekat di mata, jauh di kaki nampaknya pas buat menceritakan jarak kami dengan titik tertinggi Rinjani waktu itu.
“Bang Yos, duluan aja. Jangan tungguin gua. Jadi beban nih, gua lama”, salah satu anggota rombongan kami, Lani, mempersilakan saya melanjutkan perjalanan lebih cepat.

Bukan kali pertama saya mendengar kalimat seperti ini. Pada hari sebelumnya, satu anggota kelompok lain juga mempersilakan saya mendahului, ketika saya berjalan di belakangnya.
“Santai, gua ngga ngejar sunrise di puncak. Dari sini juga keliatan kan mataharinya. Semangat. Pasti sampe“, jawab saya sekenanya.
Sesekali, saya memang menyempatkan diri untuk berhenti di tengah jalur pendakian menuju puncak, baik untuk beristirahat sambil mengunyah roti sobek, atau untuk memotret pemandangan, manusia, atau apa saja yang sayang untuk dilalui.
Jalur yang kami lewati kian sepi. Kami malah mulai berpapasan dengan para pendaki yang sudah kembali dari puncak. Sempurna. Mengapa?
Baik, ketika saya mulai senang bepergian, mungkin ketika kuliah, beberapa teman perjalanan sering mengajak saya melihat sunrise di puncak gunung.
Awalnya saya mengikuti saja. Saya pikir memang begitu seharusnya menjadi traveler yang baik: harus tiba di puncak sebelum sunrise. Gagal tiba di puncak sebelum sunrise, berarti harus ke sana lagi suatu hari.
Saya suka melakukan summit attack pada dini hari, atau subuh. Namun kini, saya tidak pernah menargetkan untuk tiba di puncak gunung sebelum matahari terbit. Saya tidak ingin berlomba memanjat langit dengan matahari.
Alasan saya bangun untuk summit attack pada dini hari atau subuh adalah agar saya dapat kembali di pos awal pendakian lebih awal setelah turun dari puncak. Bukan untuk berdiri menatap matahari di atas sana.
Ada beberapa alasan saya memilih untuk tidak tiba di puncak gunung sebelum matahari terbit.
Pertama, saya tidak terlalu tertarik dengan sunrise. Kecuali itu adalah matahari terbit pertama di awal tahun, atau hal-hal yang terkesan filosofis lainnya, mungkin saya sedikit tertarik. Mungkin.
Namun secara umum, melihat matahari terbit adalah hal yang biasa saja buat saya. Melihat matahari terbenam sedikit lebih menarik. Sinarnya tidak terlalu menyilaukan.
Lihat juga: Cerita Foto Warna-warni Rinjani di sini.
Alasan kedua, saya tidak menganggap puncak gunung sebagai tujuan vital dan final pendakian. Hal yang saya cari di pendakian adalah suasana yang tenang, suara-suara yang tidak saya dapatkan di Jakarta, udara yang bersih, dan sebagainya.
Maka setiap jengkal, setiap langkah, setiap wilayah di jalur pendakian adalah tujuan saya. Saya harus menikmati perjalanan, dan tidak menganggapnya sebagai beban yang harus dihadapi untuk menggapai puncak. Itu salah satu alasan saya sering berhenti memotret di jalur menuju puncak.
Alasan ketiga, saya ingin menikmati suasana dan pemandangan terang di puncak gunung lebih lama.

Setelah matahari cukup tinggi, pemandangan di puncak gunung jelas akan lebih jelas. Saya sadar, saya tidak kuat terlalu lama berada di puncak gunung dengan angin yang dingin menembus jaket.
Seandainya saya hanya kuat berada di puncak gunung selama satu jam dan saya sudah tiba setengah jam sebelum matahari terbit, berarti saya hanya punya waktu setengah jam untuk menikmati pemandangan saat hari sudah terang, bukan? Iya.
“Salah satu hal yang harus kita perhatikan di sini adalah kondisi di puncak gunung. Ada gunung yang memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, pendaki dilarang berada di puncak Semeru pada waktu pagi menjelang siang, karena ada bahaya dari gas yang mematikan”.
Keempat, puncak gunung cenderung lebih ramai sesaat sebelum dan setelah matahari terbit. Riuh. Saya yakin, lebih banyak pendaki yang ingin menyaksikan matahari terbit dari puncak gunung.
Belum lagi kalau lahan di puncak tidak terlalu luas. Lahan di puncak Rinjani tak selapang di puncak Semeru, misalnya. Untuk berfoto saja, mungkin harus sabar bergiliran.
Ketika giliran tiba pun, tak bisa berlama-lama karena ada yang mengantre foto. Harapan saya, ketika saya tiba di puncak, sebagian besar pendaki sudah turun dari sana.
Lihat juga: Cerita Foto Syahdu Semeru di sini.
Jadi, itu empat alasan saya tidak pernah lagi menargetkan tiba di puncak sebelum matahari terbit, walau saya tetap selalu memulai melakukan summit attack pada dini hari atau subuh.
Bagaimana dengan Anda? Apa lebih memilih untuk menyaksikan sunrise dari puncak gunung? Tinggalkan komentar di bawah.

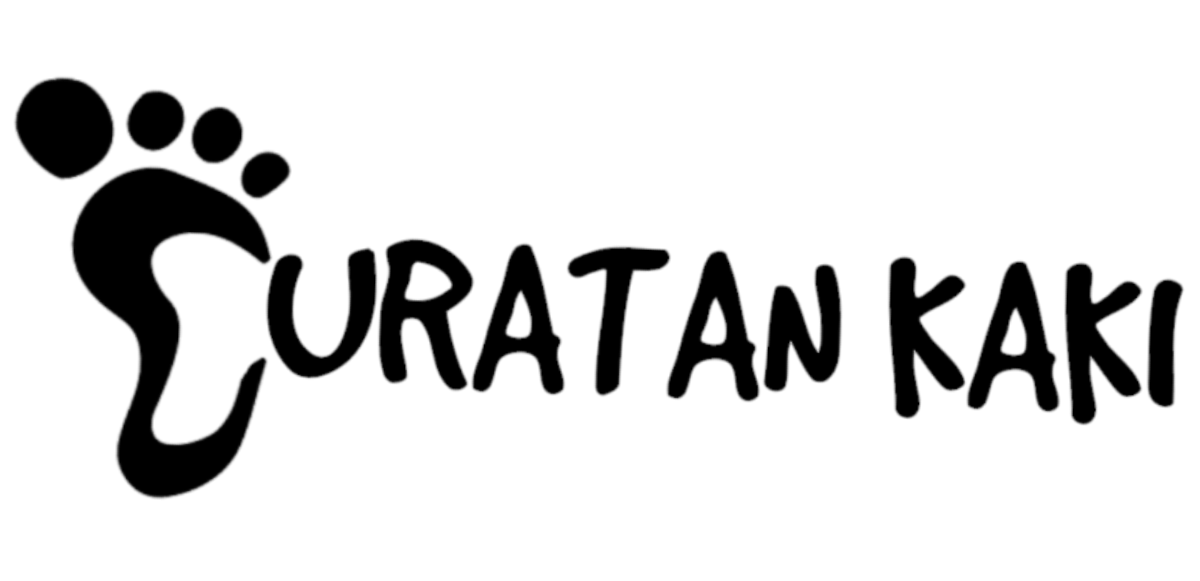

Jadi mengingatkan waktu ke Rinjani lebih dari lima tahun yang lalu. Dulu sebelum berangkat, persiapan saya sekenanya; lari pagi 1x seminggu keliling jalan-jalan kecil di sekitaran kost. Dan sebelumnya belum pernah ada pengalaman naik gunung barang satu pun. Di hari pertama mendaki badan dihajar sama tanjakan yang kayaknya gak habis-habis. Sempat kram 2x juga. Di hari kedua memutuskan untuk berhenti sampai dua pertiga jalan menuju puncak, takut malah merepotkan teman saya. Dia lanjut ke puncak, saya leyeh-leyeh duduk sendiri sambil menikmati kesunyian, dan memandangi bulan purnama yang menggantung di atas Desa Sembalun.
Pelan-pelan matahari terbit, bunga edelweiss pelan-pelan menguning terkena sinar matahari. Bayangan piramida Puncak Rinjani menutupi Danau Segara Anakan. Di sisi lain, Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air terlihat kecil. Di situ saya menyadari bahwa keputusan untuk gak memaksakan ke puncak justru menjadi berkah tersendiri. Banyak sekali keindahan yang terbentang di depan mata.
LikeLiked by 1 person
Nah kan… Suka banget nih sama komentarnya. Nanti dapet like. Bahahahaha.
Entah cuma di lingkungan saya, atau jadi “mahzab” umum, kalau ke gunung itu ya wajib ke puncak. Puncak jadi semacam tujuan klimaks yang bikin pendaki dianggap “belum ke gunung X kalau ngga sampai puncak”. Padahal ya… Ga butuh pengakuan dari orang lain juga. Bahahaha.
Waktu saya ke Rinjani juga ada beberapa temen yang bahkan ga mau naik ke puncak dan stay di Plawangan Sembalun. Keputusan mereka diambil setelah masing-masing menakar kemampuan diri. Intinya sama, ga mau ngerepotin orang. Akhirnya, mereka bisa nikmatin Plawangan Sembalun yang sunyi dan tenang.
LikeLiked by 1 person
acung jempol telah bisa menaklukann rinjani, waktunya menaklukkan hati si kakak 😀 hehhe
LikeLike
Taklukkan hati tante… *perebut bini orang*
LikeLike
Saya tim yang menyaksikan matahari terbit dari jendela kamar saja, Kak! Lahir di Lombok membuat saya bisa berbangga sebagai “anak-anak Rinjani” ya tapi belum pernah melihat matahari terbit pula di sana, kan malu-maluin yak, hehe. Saya sangat setuju dengan filosofinya, matahari terbit saja sudah sesuatu yang harus disyukuri, bagi saya sendiri tak usah menodai rasa syukur itu dengan beban harus melihat terbitnya surya dari ketinggian sekian dan sekian… ah yang penting hari ini masih bisa bernapas dan berkontribusi…
LikeLiked by 1 person
Wah, saya udah main ke Lombok tapi belum sowan ke tuan rumah nih 😛
Haha ya ngga malu-maluin lah, Mas Gara. Preferensi wisata kan beda-beda. Semoga pemandangan dari jendela rumahnya tetep asoy 😀
LikeLike
Tuan rumahnya lagi ada di ibukota, Kak, haha.
Tetap indah, tentu saja. Paling tidak bisa membuat saya bersyukur, hehe.
LikeLike