Lonceng di Balai Kota berdentang nyaring pagi itu. Tanda ada nyawa yang akan binasa. Seutas tali siap menggiring narapidana ke pintu ajal.
 |
| Museum Fatahillah di kawasan wisata Kota Tua Jakarta menjadi salah satu lokasi wisata kesukaan warga Jakarta. |
Sudah sekitar separuh jam saya berada dalam bangunan ini, di Museum Fatahillah, Jakarta. Panas cuaca di luar seolah membuat saya merasa lebih betah di dalam. Adem. Langit-langit Museum Fatahillah menggantung tinggi, membuat udara bersirkulasi dengan baik.
Nuansa klasik juga begitu terasa. Dinding tebal berwarna putih pucat, serta lantai parquet hampir di seluruh ruangan. Khas Belanda. Iya, bangunan berusia sekitar 300 tahun, dengan arsitektur bercita rasa Belanda yang begitu kental. Perabotan di lantai dua disusun rapi. Meja, kursi, dan almari berwarna cokelat gelap, konon digunakan oleh pemerintah Belanda di Batavia pada abad XVIII.
Di beberapa ruangan, lukisan-lukisan pejabat Belanda dipajang, seakan tengah memperhatikan tingkah laku para pengunjung agar tak melakukan vandalisme. Pada ruangan lain, mata saya menangkap sebuah daun pintu menuju anak tangga. Tertutup rapat, dengan pengait gembok yang sudah rusak. Tanpa gagang pintu. “Perhatian. Dilarang masuk selain petugas. Terima kasih”, demikian tertera di kertas yang melekat di sana.
Saya membayangkan, tangga ini akan membawa saya menuju lonceng bersejarah di gedung ini. Lonceng yang dulu berdentang sebelum nyawa binasa. Saya melempar pandangan ke sudut langit-langit ruangan ini. Ada kamera pengawas. Seketika saya teringat pengakuan seorang polisi Perancis, Captain Bezu Fache kepada Profesor Robert Langdon dalam novel Da Vinci Code. Kamera pengawas di Museum Louvre bukanlah kamera sungguhan. Begitu katanya. Ah, saya di sini mencari kesenangan, bukan masalah. Niat untuk menyusup saya tinggalkan di sana.
 |
 |
| Salah satu ruang rapat Dewan Kotapraja Kota Batavia |
 |
| Wisatawan asing sedang menelusuri ruangan-ruangan di dalam Museum Fatahillah |
 |
| Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coon |
Lantai parquet berderit-derit ketika saya berjalan menuju balkon lantai dua. Dari sini, lapangan di depan Museum Fatahillah terlihat jelas. Saya memandang menembus kaca. Beberapa kendaraan lalu lalang di Jalan Cengkeh, tepat di depan lapangan. Mungkin akan menuju Pelabuhan Sunda Kelapa yang berjarak tak jauh dari sini. Pandangan saya kini melekat ke lapangan.
Dari depan jendela yang tertutup, saya bisa merasakan udara dari luar menyelinap lewat sela jendela. Segar. Tiga abad lalu, yang berdiri di sini ialah para hakim Dewan Pengadilan kolonial Belanda. Mungkin bukan hanya angin segar yang mereka rasakan masuk dari jendela waktu itu. Tapi juga bau amis dan suara isak tangis. Bau amis darah para terpidana pemerintah Belanda, serta isak tangis kerabat yang tak rela.
Di bawah, di lapangan, ada beberapa wisatawan memasang pose ceria. Ada di antaranya yang berpose seperti model kalender jaman purba, entahlah, di depan meriam. Ada pula sekelompok wisatawan yang berfoto bersama pria berkostum khas Dinasti Qing, meniru hantu vampir seperti di film.
Salah satu di antaranya mengangkat pedang —tentu saja pedang mainan– dan bergaya seperti hendak menghunus ujung pedang di leher si vampir. Mereka terbahak, nampak bahagia. Mungkin kontras dengan suasana pada 119 tahun sebelumnya.
Sekitar satu abad lalu, di tempat yang sama, seorang pemuda bernama Tjoen Boen Tjeng dieksekusi mati di sini. Dihukum mati dengan cara digantung di muka umum. Pengadilan Belanda memvonis Tjeng dengan hukuman gantung atas dugaan perampokan dan pembunuhan terhadap dua perempuan. Sejarah mencatat, eksekusi mati terhadap Tjeng ini adalah ekseskusi mati terakhir yang dilakukan pemerintah Belanda di muka umum. Setelah Tjeng, para terpidana hukuman mati lainnya menghadapi jeratan tali gantung atau tebasan pedang di tempat tertutup.
 |
| Wisatawan sedang melintasi lapangan Museum Fatahillah. Lapangan ini sempat dijadikan tempat pelaksanaan hukuman mati terhadap para narapidana oleh pemerintah kolonial Belanda. |
 |
| Seorang pria menggunakan kostum hantu vampir tengah berfoto bersama sejumlah wisatawan. |
Pada abad XVIII, gedung Museum Fatahillah berfungsi sebagai kantor pemerintah Belanda di Batavia, atau dalam bahasa Belanda disebut stadhuis. Gubernur Jenderal John van Hoorn yang memerintahkan pembangunan stadhuis pada tahun 1707. Kini, perabotan antik bekas pemerintahan Belanda dipamerkan di lantai dua. Sisi lain gedung digunakan sebagai ruang pengadilan. Para terdakwa kala itu mungkin tidak seperti para terduga kasus korupsi masa kini—yang tahu akan mendapat vonis ringan–di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Dulu, hukuman mati kerap dijatuhkan di sini. Sambil menunggu mendapat vonis hakim, para terpidana akan menanti ajal di ruang penjara bawah tanah. Letaknya di bagian belakang bangunan museum. Ada lima ruangan penjara bawah tanah berukuran sekitar empat kali empat meter persegi. Tinggi langit-langitnya? Jangan dibandingkan dengan ketinggian langit-langit Museum Fatahillah. Ketinggian langit-langit ruangan penjara bawah tanah hanya sekitar 170 cm. Masing-masing ruangan memiliki satu pintu masuk dan satu jendela besar, jendela yang ditutup dengan dua lapis teralis besi. Temboknya cukup tebal, mungkin dari setengah meter. Rasanya para tahanan butuh upaya dan waktu ekstra untuk membobol tembok ruang tahanan.
Tapi nampaknya pemerintah Belanda saat itu masih khawatir para tahanan akan melarikan diri. Para tahanan pada saat itu akan dipasangi bola besi yang diikat ke kaki mereka agar mereka sulit melarikan diri. Melarikan diri dari penjara, dan tentu saja, dari tiang gantungan.
Menurut arsip sejarah, hukuman gantung menjadi salah satu cara pemerintah Belanda di Batavia untuk mengantar para narapidana ke pintu ajal. Namun, senapan dan pedang juga kadang digunakan untuk membuat terpidana binasa. Pedang Keadilan. Demikian mereka menyebutnya. Pada satu sisi pedang tertera tulisan berbahasa Belanda yang artinya,”Jagalah bicaramu agar tidak dihukum oleh pengadilan ini“. Tulisan pada sisi lainnya lebih membuat saya tergelitik, “Tuhan, mohon ampun untuk pendosa ini“.
27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda angkat kaki. Lonceng di Museum Fatahillah tak lagi berbunyi. Tapi tak berarti palu hakim berhenti mengetuk vonis hukuman mati. Museum Fatahillah bukan warisan semata wayang yang ditinggalkan kolonial Belanda di Indonesia. Sistem hukum Belanda juga terisa, termasuk hukuman mati, hukuman yang sudah ditinggalkan pemerintah Belanda sejak tahun 1992.
 |
| Ruang penjara bawah tanah yang terletak di sisi belakang Museum Fatahillah. |
 |
| Mata pedang yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengeksekusi mati para narapidana. |
 |
| Menara lonceng di atas Museum Fatahillah. Lonceng akan dibunyikan pada pagi hari, sebelum ekskusi mati digelar di depan publik. |
 |
| Tjoen Boen Tjeng, pemuda terakhir yang dieksekusi mati pengadilan d depan publik pada tahun 1896. Setelah ini, semua eksekusi mati dilakukan pengadilan di tempat tertutup. |

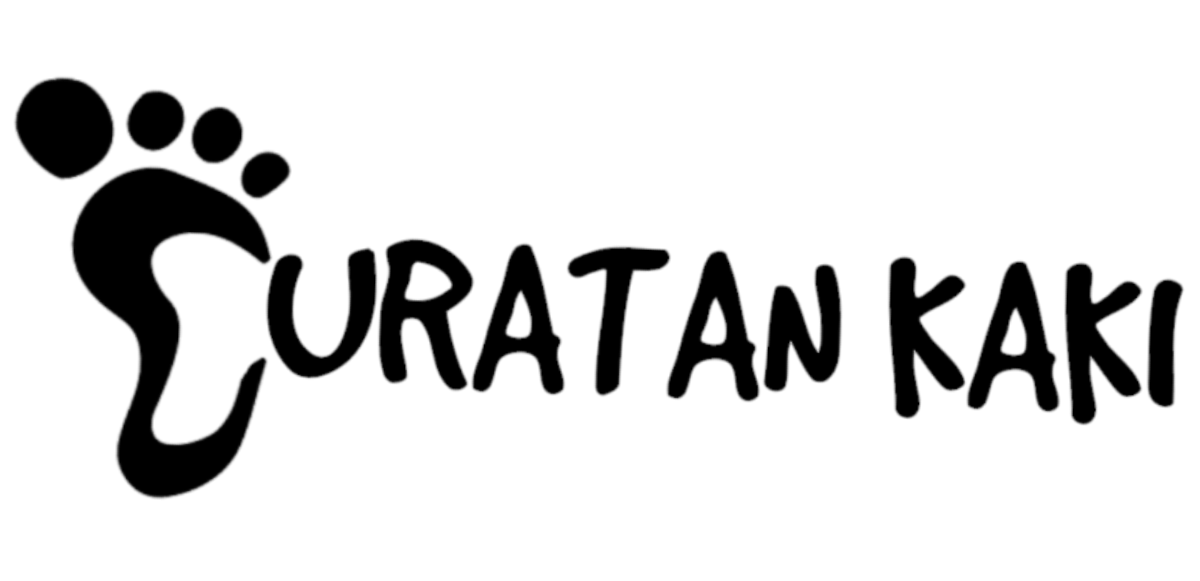


Wah, lonceng Soli Deo Gloria yang cetar membahana. Saya kalau malam berkunjung ke Stadhuisplein ini juga ikut membayangkan, dulu waktu lonceng ini berbunyi, orang-orang yang mendengar bukannya senang, malah gentar dan berpikir, “Hari ini siapa lagi yang dieksekusi?” Entah bagaimana perasaan orang-orang yang melihat eksekusi itu berlangsung… :huhu. Tulisannya mantap, Mas!
LikeLike
Oya? Itu nama loncengnya? Baru tau. Haha.. Membawa nama Tuhan untuk menghakimi manusia juga jadi salah satu warisan Belanda yang mengakar di sini ya? Haha.
Terima kasih sudah mampir, Kakak Gara.
LikeLiked by 1 person
Mungkin, karena setiap putusan pengadilan pasti punya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan irah-irah itu menjadi legitimasi karena betapapun putusannya, tanpa satu kalimat itu kan jadi tidak sah dan batal :hihi.
Sama-sama, Mas! Senang rasanya bisa belajar juga dari tulisan ini :)).
LikeLike
Bangunan saksi sejarah Indonesia, kadang suka speechless liat bangunan kota tua ini, mulai dari arsitektur bangunan sampe barang2 peninggalan kompeni dulu kagum banget 😮
LikeLike