Jarak pandang di depan saya makin terbatas. Mungkin hanya 50 meter. Saya berjalan menembus kabut. Atau awan. Entah.
Gelap akan segera menelan hari. Saya tidak menyangka medan pendakian akan begitu sulit. Jalan setapak juga makin sempit, tak lebih dari lima meter. Kiri kanan jurang. Tak tahu berapa dalam. Kabut benar-benar menutup pandangan.
Kadang pohon merintang, hingga saya harus berjalan mengitari pohon. Tiba-tiba sroottttt! Tanah yang saya pijak longsor. Saya terperosok. Tangan kanan saya mencengkram kuat batang pohon yang tadi berusaha saya lalui. Saya menggelantung. Saya gemetar. Saya hampir mati dua kali dalam satu bulan.
“Tim evakuasi masih berusaha mengangkat jenazah dari titik jatuh pesawat Sukhoi Superjet 100 di lereng Gunung Salak. Menurut Basarnas, titik jatuhnya pesawat berada sekitar 400 meter di bawah bibir jurang. Hampir tegak vertikal. Diperlukan teknik khusus untuk mencari dan membawa para korban di dasar lereng. Demikian, kembali pada Anda di studio,” saya menutup laporan langsung.

Senin, 14 Mei 2012. Sudah tiga hari saya bolak-balik ke sini, ke sebuah lapangan bola di belakang SMP Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lima hari lalu ada kabar haru. Pesawat Sukhoi Superjet 100 celaka di Gunung Salak. Pesawat jatuh setelah menghantam lereng dalam misi demonstrasi penerbangan komersil.
Sekitar 50 orang dalam pesawat meregang nyawa. Pilot, pramugari, pejabat maskapai domestik, hingga para wartawan. Malam dan pagi kami di Cijeruk seakan tak bersekat. Ada yang terjaga, ada yang tertidur berselimut duka. Tak rela meliput rekan sesama wartawan tewas dalam kecelakaan.
Panggilan telepon dari Jakarta juga tak jemu menyapa. Terus berdering, meminta perkembangan informasi. Korban, kotak hitam, upaya pencarian, upaya pengangkatan korban —Jakarta tidak pernah berhenti menagih informasi dari lapangan.
Saya menunggu kabar yang sungguh, tidak ingin saya dengar. Kabar yang harus saya sampaikan kepada para anggota keluarga penumpang melalui layar kaca. Kabar mengenai penemuan para penumpang yang sudah menjadi korban.
Semua informasi harus diversifikasi, tentu. Peristiwa tragis seperti ini kerap dimanfaatkan oleh orang bodoh dengan ponsel pintarnya untuk menebar sensasi, seperti foto yang bisa membuat tangis pecah di lingkungan keluarga dan kerabat korban, atau kabar burung tentang ponsel penumpang yang masih aktif, yang tentu, membuat spekulasi liar menyudutkan pihak tertentu.
Setiap kali ada penemuan jenazah yang mengantungi identitas pribadi, hati terenyuh. Pilu. Ada sensitivitas hati yang semakin peka ketika saya merasa sedih akan sesuatu hal yang menimpa seseorang yang tidak saya kenal, sekali pun. Bagaimana saya harus menyampaikan informasi ini di depan lensa kamera?
60 kilometer dari tempat saya melaporkan, di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, para anggota keluarga penumpang sedang memandangi layar televisi. Menunggu kabar baik. Menanti mukjizat. Hingga satu-persatu harapan menanti anak untuk pulang silih berganti menjadi kepasrahan.
“Tuhan, bantu lidah saya menyampaikan informasi ini kepada mereka. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi anggota keluarga yang menunggu berita. Berita yang pasti, tidak ingin mereka dengar. Setiap kalimat, setiap kata, harus disampaikan dengan empati”.
Malam itu, seperti biasa, kami tengah menikmati makan malam di rumah yang kami sewa, tak jauh dari SMP Negeri 1 Cijeruk. Saya bersama belasan rekan kerja dari kantor di Jakarta menyewa sebuah rumah warga di sana. Pemilik rumah begitu ramah dan sigap menyediakan semua keperluan kami.
Ada yang spesial hari ini. Derie Imani, rekan sesama jurnalis dari kantor kami, sudah kembali dari pendakian. Ia sudah beberapa hari menelusuri hutan Gunung Salak. Lahap sekali ia makan. Derie berbagi cerita dan informasi tentang jalur pendakian yang akan saya tempuh besok. Saya akan menggantikan Derie menelusuri pencarian para korban.
Terdengar mudah. Namun ternyata, perkiraan saya meleset.
♦♦♦
Saya bersama Mas Itok, juru kamera, memulai perjalanan pagi keesokan harinya. Kami berangkat melalui jalur Curug Nangka. Kami akan mendaki menuju lereng Puncak I Gunung Salak dari sisi utara gunung.
Untuk tiba di sana, kami harus melalui Puncak II. Tentu kami tak sendiri. Tiga orang warga setempat menemani perjalanan kami. Pak Mahdi salah satunya. Ia yang tertua di antara mereka bertiga, memimpin perjalanan kami. Ternyata medan yang kami tempuh tak mudah. Terlebih, bagi Mas Itok yang harus berhati-hati membawa kamera. Kami menembus hutan tropis di Gunung Salak.
Baca juga: Wawancara Nyomie, dokter hewan yang membawa anak balitanya ke puncak-puncak gunung. Klik di sini.
Pepohoan begitu subur tumbuh di sini. Akar pohon besar-besar juga kerap merintangi perjalanan kami. Beruntung, panas tak terasa di bawah kanopi pepohonan. Kalau tanjakan saja, mungkin saya bisa cepat berjalan. Entah berapa kali saya harus berhenti berjalan karena kaki keram.
Akar pepohonan tak jarang harus saya cengkram kuat untuk memanjat, bukan mendaki. Bebatuan pun tak jarang harus saya pijak untuk meniti jalan sambil merapatkan badan ke tebing. Ini adalah pendakian perdana yang saya lakukan. Saya tidak pernah mendaki gunung sebelum ini. Tapi entah, semangat begitu bergelora. Target kami, bermalam di Puncak II Gunung Salak.
Siang sudah hampir lewat. Kalau tidak salah sudah sekitar pukul empat sore. Kami hampir tiba di Puncak II, tempat kami akan mendirikan tenda. Jarak pandang di depan saya makin terbatas. Mungkin hanya 50 meter. Saya berjalan menembus kabut. Atau awan. Entah.
Saya tidak menyangka medan pendakian akan begitu sulit. Badan tak terlalu letih, tapi konsentrasi –yang ternyata sangat diperlukan di bagian perjalanan ini– mulai buyar. Jalan setapak makin sempit, tak lebih dari lima meter. Kiri kanan lereng terjal, yang lebih nampak seperti jurang. Tak tahu berapa dalam. Kabut benar-benar menutup pandangan.
Suara hewan, mungkin kera, saya tak yakin, bersahutan dari bawah selimut kabut. Bergaung. Kadang pohon merintang, hingga saya harus berjalan mengitari pohon. Tiba-tiba sroottttt! Tanah yang saya pijak longsor. Saya terperosok. “Ya Tuhan! Mas Itok, pegangin!!”.
Tangan kanan saya mencengkram kuat batang pohon yang tadi berusaha saya lalui. Sekuat tenaga. Saya panik. Saya hampir mati dua kali dalam satu pekan terkahir, yang pertama tidak jadi, kali ini? “Buang aja tongkatnya!”, Mas Itok yang posisinya paling dekat mencoba meraih tangan kiri saya. Pak Mahdi membantu Mas Itok menarik. Saya tidak jadi mati, lagi.
♦♦♦
“Yos, saya tuh hampir nugasin kamu ikut joy flight Sukhoi kemarin. Untung ga jadi”.
Kalimat itu kembali terlintas dalam benak.Sebenarnya saya nyaris menjadi salah satu wartawan yang mendapat tugas untuk ikut dalam demonstrasi penerbangan Sukhoi Superjet 100. Membuat laporan mengenai persaingan bisnis pesawat komersil tanah air —yang selama ini dikuasai oleh produsen dari Amerika dan Eropa.
Sebelumnya, industri pesawat asal Rusia ini lebih akrab dikenal sebagai penghasil pesawat militer. Namun, Sukhoi juga sebenarnya menjalankan bisnis pesawat komersil, Sukhoi Civil Aviation. Pesawat komersil inilah yang akan dijual secara lebih gencar ke negara-negara di Asia. Negara-negara di Asia dianggap sebagai pasar yang memberi janji manis, di tengah keterpurukan perekonomian global. Pasar Indonesia pun tak luput dari incaran Sukhoi.
Beruntung, koordinator peliputan membatalkan penugasan saya. “Kita lagi kekurangan tim di Jakarta,” katanya menjelaskan alasan pembatalan.
♦♦♦
Dari sini, saya berjalan ekstra hati-hati. Syukur, kami tiba di Puncak II sebelum tiba gulita. Kami mendirikan kemah. Kemah seadanya. Membentangkan terpal dan mengikatnya di pepohonan. Tak lama, tenda bivak pun jadi. Pak Mahdi juga sudah selesai mengumpulkan ranting kering untuk membuat api.
Dari sini, saya bisa melihat Puncak I Gunung Salak. Tak jauh dari sana, saya melihat bekas longsoran di lereng dekat Puncak I. Cokelat tanah membekas di antara hijau pepohonan. Membentuk garis lurus vertikal. Seperti bekas digaruk benda berukuran besar. Saya mengira, itu adalah lereng yang dihantam pesawat.
Saya merinding membayangkan detik-detik menjelang kecelakaan. Saya merinding mengingat pembatalan penugasan saya mengikuti penerbangan itu. Apa yang akan saya lakukan pada detik-detik sebelum pesawat menghantam lereng? Siapa yang akan saya ingat ketika pesawat tiba-tiba menukik ke atas untuk menghindari maut?

Langit kelabu petang itu. Suram. Gunung Salak ingkar janji. Ingkar dari namanya sendiri. Sebagian masyarakat Jawa Barat percaya, Gunung Salak adalah tempat singgah para dewa di tanah para dewa, atau parahyangan.
Pesona lerengnya yang memantulkan cahaya matahari pagi dan sore membuat masyarakat menyebutnya sebagai Gunung Salak, dari kata Salaka, yang berarti perak dalam Bahasa Sansekerta. Tapi sekali lagi, panorama di lereng Gunung Salak benar-benar tak memesona sore itu.
Dari kejauhan, saya dengar langkah kaki. Kami tak sendiri malam itu, beberapa anggota tim evakuasi dari TNI juga bermalam di Puncak II. Kami berbagi perbekalan. Untuk pertama kalinya pula, saya mencicipi, atau tepatnya, menghabisi makanan kalengan untuk tentara. Ransum.
Cara memasaknya unik. Buka sedikit, lalu taruh di atas api. Tak lama, ransum sudah dapat dinikmati. Saya banyak bertanya kepada para tentara, sambil menikmati kopi malam, hingga akhirnya kantuk menggelantung di pelupuk mata.
malam hening. ada angin kering, dingin. di mana aku? mengapa dingin di sini?
selimutku kabut tebal berkemelut kalut
dingin, sunyi di sini. sepi sekali takut aku sendiri
aku terbaring, bertabur puing
nadiku beku. selimutku kabut. cungkupku malam
Lalu aku lihat maut menyambut, perempuan hitam berkerudung kabung
sayup kudengar isak haru mendayu, lagu-lagu syahdu
Jakarta, 24 Mei 2012
Iyos Kusuma
Entah berapa jam saya tertidur. Rasanya tak cukup. Beberapa kali saya terbangun karena tak tahan pada dingin. Pagi itu, tak ada alasan, perjalanan harus dilanjutkan. Ini adalah penugasan, bukan liburan.
“…kami akan melanjutkan perjalanan menuju bibir jurang yang berada di dekat Puncak I Gunung Salak. Di sana, tim evakuasi masih berusaha menggapai dasar jurang untuk mencari seluruh korban …”
Demikian saya memulai laporan pada pagi itu. Bukan siaran langsung, tentu saja. Sejak awal, kami mendokumentasikan perjalanan untuk nanti dikirim ke Jakarta. Rencana kami ialah melakukan laporan langsung dari bibir jurang. Tempat para anggota pasukan elit TNI AD, Kopassus, menuruni lereng curam dengan kemiringan hingga 80°. Nyaris vertikal.
Saya sudah mulai terbiasa untuk berurusan dengan medan perjalanan. Dari Puncak II, saya harus menuruni lereng gunung dan kemudian mendaki lagi untuk menggapai Puncak I. Sesekali, helikopter nampak melintas, untuk mendarat di Puncak I. Menjemput jenazah yang sudah diangkat dari lereng, atau dasar jurang.
Memasuki jalur pendakian menuju Puncak I, medan semakin curam. Batu dan akar menjadi pegangan dan pijakan untuk memanjat. Beberapa kali, barisan tim SAR menyalip kami.
Seringkali mereka mengulurkan tangan dari atas bebatuan untuk menarik saya naik. Tak jarang pula mereka menawarkan air kepada kami. Sumber air tak ada di sini. Tapi di sini, botol air kerap berpindah tangan, kenal atau tidak kenal. TNI, polisi, relawan, wartawan, semua dipersatukan oleh solidaritas. Tak peduli kamu siapa saya siapa.
Hari sudah mulai siang. Tapi matahari nampak tak begitu bersemangat. Malah mendung. Kami terus berjalan, sampai akhirnya terhenti di kerumunan. Ada apa? “Itu di situ ada puing-puing pesawat, Mas”, jawab salah satu tentara yang tengah beristirahat. Jantung seketika berdetak kencang. Saya yakin, waktu itu saya merinding bukan karena udara dingin.
Saya tidak peduli Anda menyebut saya berlebihan ketika mengingat ‘pengalaman tidak jadi mati’ membuat kaki saya lemas waktu itu. Saya berjalan mendekati kerumunan. Saya lihat Mas Itok sibuk merekam aktivitas tim SAR. Di sana porak poranda. Serpihan beberapa bagian pesawat tersebar. Bagian pintu pesawat, lempengan putih badan pesawat, serta kerangka pesawat berwarna hijau.
Tak jauh dari sana, barang-barang penumpang berantakan. Saya melihat ada brosur penerbangan, alat kosmetik, sobekan beberapa helai pakaian. Ya Tuhan… Saya tak kuat untuk melanjutkan melihat-lihat. Sesekali angin dari lereng membawa aroma menyengat. Aroma yang saya kenal betul. Ya Tuhan. Kaki benar-benar lemas. Saya duduk bersandar di batang pohon.
Di depan saya, tim SAR datang mendekat. Mereka membawa suatu benda berwarna hitam dan jingga menyala. Kantong jenazah. Semua kantong jenazah yang sudah diangkat dari lereng dan dasar jurang dikumpulkan di Puncak I. Helikopter akan terbang ke sana untuk membawa kantong-kantong jenazah ke helipad di lapangan SMP Negeri 1 Cijeruk.





Dokumentasi kegiatan pencarian cukup, kami melanjutkan perjalanan. Tidak terlalu jauh menuju puncak dari sana. Hanya medannya semakin sulit. Bebatuan yang sangat curam, hampir vertikal, harus kami lalui sambil mencengkram tambang. Langit semakin mendung. Kami bergegas. Kami tak ingin memanjat bebatuan ini di bawah guyuran hujan. Pasti licin dan berbahaya.
Akhirnya kami tiba di Puncak I sekitar pukul 14:00. Orang-orang sibuk di atas puncak. Ramai. Saya menemukan wajah-wajah letih para relawan, para anggota tim SAR gabungan, dan juga wartawan. Semua bekerja sesuai peran masing-masing.
Sudah ada sekitar tiga atau empat kantong jenazah di sana. Mungkin empat, saya lupa. Di atasnya suara baling-baling helikopter berbunyi kencang. Satu persatu, semua kantong jenazah diikat dan diangkat masuk ke badan helikopter dengan menggunakan tali. Tak lama, helikopter pergi.
Baca juga: Menyusuri sisa letusan gunung purba di Gunung Rinjani. Klik di sini.
Tak lama pula, hujan turun mengguyur. Kami berhamburan. Mencari tempat berteduh. Saya menumpang di bawah terpal tim SAR. Saya membuka botol yang sudah kosong dari tadi. Menampung air yang menetes dari pepohonan. Meneguknya. Terasa dingin, segar sekali. Alam menyediakan air untuk kami minum. Sebelum hujan reda, saya harus memastikan perbekalan air cukup.
Sebotol penuh sudah terisi air hujan. Cukup. Kata salah seorang anggota tim SAR, perjalanan menuju Cimelati tak begitu jauh. Kami bisa tiba di sana sebelum gelap.
Hujan reda. Kami malanjutkan perjalanan. Kami akan turun dari sisi barat Gunung Salak, lewat Desa Cimelati di Kabupaten Sukabumi. Jalan terus menurun. Kami jalan cepat, cenderung berlari. Perasaan saya campur aduk. Letih, lapar, sedih, takut, semua jadi satu. Entahlah. Saya terus berlari menuruni lereng gunung. Pak Mahdi di mana, Mas Itok di mana, saya tidak tahu. Entah di depan atau di belakang saya.
Kaki mulai sakit, saya tidak peduli. Saya lapar ingin segera tiba di desa untuk makan telur dadar kesukaan saya di warung makan. Pepohonan liar pegunungan berganti jadi hutan produk perhutanan. Kiri kanan pepohonan. Bayangannya panjang-panjang, seperti hangat matahari sore menepuk lembut setiap batang. Pohon apa, tak tahu. Tapi semuanya ditanam rapi. Berjarak teratur satu sama lain. Suara deru motor sayup terdengar. Saya semakin dekat.
Di depan, tenda-tenda berwarna jingga mulai terlihat. Warna jingga khas Basarnas. Terima kasih, Tuhan, saya tiba di Desa Cimelati. Beberapa hari ini menjadi hari-hari yang tidak mungkin saya lupakan. Pembatalan penugasan untuk ikut dalam joy flight. Laporan langsung tiada henti di Cijeruk. Pengalaman pertama menembus hutan pegunungan. Mempertaruhkan nyawa dengan mencengkram batang pohon di bibir lereng curam. Meneguk tampungan air hujan yang ternyata penuh lumut setelah diperhatikan dari dekat.
Saya menatap ke belakang. Gunung Salak tak muram sore itu. Memantulkan cahaya matahari sore yang sebentar lagi terbenam. Indah. Salaka seperti bagaimana disebut oleh masyarakat sekitar pada masa lalu.

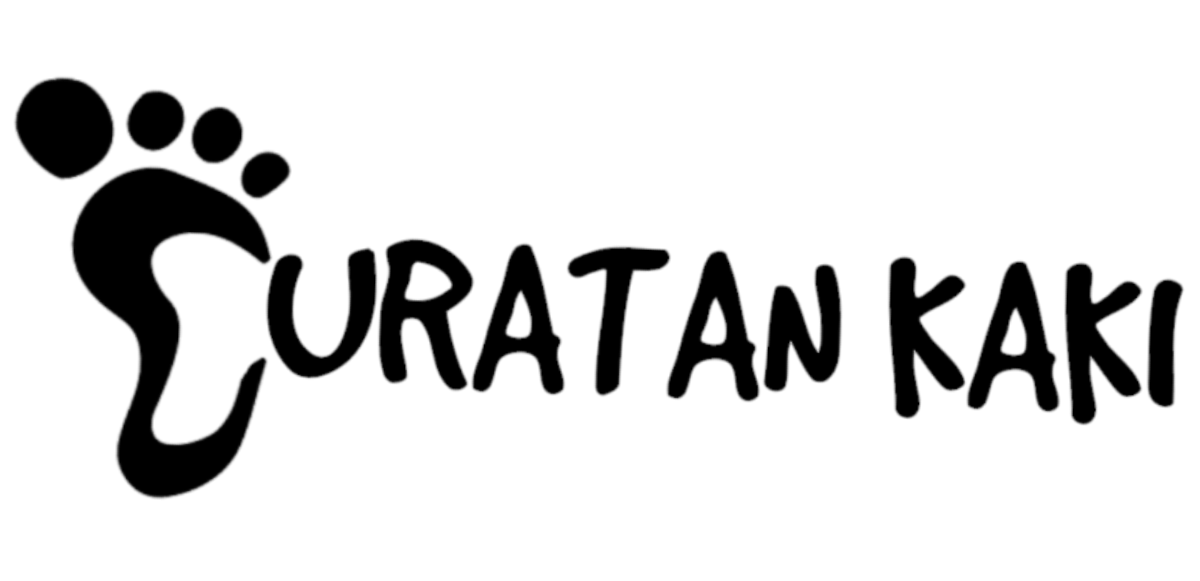


Jika memang kondisi para pendaki fit, dari Desa Girijaya menuju Puncak Salak 1 dapat ditempuh dalam waktu sekitar 5 jam. Jika fisik oke, kita bisa membuat camp untuk bermalam di Puncak Salak 1, namun jika kondisi fisik team tidak memungkinkan, pondokan di fly camp bisa dijadikan alternatif untuk bermalam. Satu yang harus kita perhatikan, jangan lupa bawa kembali sampah turun serta jaga etika kita selama mendaki gunung salak. Percaya atau tidak, kita memang hidup berdampingan dengan mahkluk ghaib lainnya. Selamat mendaki!
LikeLike
Semoga Allah memberikan maghfirahNya kpd hambanya yg ikhlash dalam penerbangan komersial dan bagi kita sekuanya adalah mauizzah hasanah 🤲🤲🤲
LikeLike
Aamiin.. 🙏
LikeLike