“Apa, Mas, ketemu?”, todong saya memotong perbincangan Mas Parno dengan adiknya.
“Ketemu, Mas. Jatuh di air terjun”, jawabnya sambil menunjukkan beberapa foto dari grup perbincangan WhatsApp. Foto tubuh manusia tergeletak di antara bebatuan. “Meninggal”, tambahnya.
Suasana dingin di pintu masuk jalur pendakian New Selo seakan kian terasa.
“Kemungkinan dia mau coba motong jalur, biar deket. Tapi ya ngga tau, itu perkiraan”, sambungnya.
“Berarti Gunung Mebabu udah buka, ya?”, tanya saya lagi.
“Mulai besok buka, Mas”, jawabnya singkat.
Kami baru akan memulai pendakian Gunung Merapi siang itu. Saya bersama dua orang teman, Yan Rahman dan Igna Ardiani.
Sambil menyantap makan siang, kami membahas rencana kami setelah turun dari Merapi siang besok, lanjut ke Merbabu atau tidak.
Kami menunda untuk mengambil sikap. Keputusan kami: keputusan untuk melanjutkan pendakian ke Merbabu baru akan diambil setelah kami turun dari Merapi. Melihat kondisi fisik dan cuaca.
Sejak awal merancang rencana pendakian, kami sebenarnya lebih memilih untuk mendaki Merbabu terlebih dahulu. Namun, jalur pendakian Merbabu ditutup sejak beberapa hari sebelum kedatangan kami. Ada pendaki dari Selandia Baru yang hilang.
Ternyata, bukan hanya kami yang terpaksa banting setir ke Merapi. Beberapa pendaki yang kami jumpai juga bernasib sama. “Masnya pasti mau ke Merbabu ya sebenarnya?”, begitu tanya mereka sambil nyengir.

“Oke, Mas. Besok tolong jemput di sini lagi sekitar jam makan siang, ya”, kami berpamitan kepada Mas Parno lalu memulai pendakian.
Sejak erupsi Merapi terjadi pada 2010, jalur pendakian Merapi dari Desa Kinahrejo di selatan Merapi ditutup. Jalur yang kami lalui ini—New Selo di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu—adalah salah satu jalur resmi yang masih dibuka.
Selain jalur pendakian dari Selo, ada pula jalur pendakian dari Kecamatan Kemalang di Klaten. Jalur Sapuangin namanya. Kemarin, saya berbincang dengan beberapa pengurus Taman Nasional Gunung Merapi di Jakarta. Ternyata, jalur Sapuangin ini adalah jalur lama yang sempat ditutup akibat erupsi Merapi. Baru pada Mei 2017, jalur ini dibuka kembali.
Erupsi Merapi pada 2010 tercatat sebagai erupsi terbesar Merapi sejak 130 tahun terakhir. Berbeda dengan erupsi Merapi pada biasanya yang berupa erupsi lelehan atau guguran, erupsi pada tahun 2010 adalah erupsi letusan. Tak hanya mengubah bentuk fisik Merapi, erupsi pada 2010 juga merusak sekiranya 30% kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
Awan panas dengan suhu sekitar 900-1.200ºC membumbung hingga mencapai 7,5 kilometer dan meluncur hingga sejauh 19 kilometer. Bergulung-gulung menerjang apa pun yang ada di depannya: manusia, hewan ternak, permukiman. Masyarakat setempat menamakannya wedhus gembel. Sedikitnya 300 orang tewas. Lebih dari 61.000 orang mengungsi.
Jalur semen yang terus menukik naik menjadi medan awal pendakian. Kami melewati perkebunan selada milik warga yang berada di sisi kanan jalur pendakian. Sesekali kami juga berpapasan dengan para petani yang baru kembali dari ladang mereka.
Tidak mengherankan jika warga banyak bercocok tanam di sini. Tanah di kaki Gunung Merapi begitu gembur. Label “gunung berapi teraktif di Indonesia” yang dinobatkan kepada Gunung Merapi seakan memberi jaminan hidup kepada sekiranya 40.000 warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Kian jauh kami mendaki, ladang milik warga sudah tidak lagi kami dapatkan. Pintu masuk Taman Nasional Gunung Merapi jadi batas perkebunan warga. Pemandangan pun beralih dari perkebunan menjadi pepohonan pinus.
Di sini ada dua pos mungil yang dapat dipakai rehat oleh para pendaki. Ada pula warung darurat yang menjual makanan dan minuman seadanya. Kami juga mendapati sebuah papan informasi yang menjelaskan rute pendakian. Jarak dan waktu tempuh pendakian tertera di sana.
Berlandaskan keterangan ini, kami harus melewati pos pertama dan pos kedua, sebelum kami tiba di Pasar Bubrah, tempat kami berencana mendirikan kemah. Jangan bayangkan pasar tradisional. Pasar Bubrah cuma nama saja.
Memasuki kawasan taman nasional, medan pendakian masih tak mencoba ramah sedikit pun, terus menanjak. Jalur semen tentu tak lagi kami temukan di sini. Jalur yang kami pijak adalah tanah padat dan bebatuan.

Jalur terus menanjak, tanpa ada “bonus” yang berarti. Pada beberapa bagian jalur pendakian, kami harus berhadapan dengan medan bebatuan yang sungguh terjal. Kami tak bisa mendaki, harus sedikit memanjat. Napas saya tersengal dibuatnya.
Benar kata orang, “apalah arti sebuah angka mdpl?”.
Jika dilihat dari angka ketinggian, Gunung Merapi bukanlah apa-apa. Namanya tidak bertengger di jajaran nama “seven summit” Pulau Jawa. Ketinggiannya tak genap 3.000 meter di atas permukaan laut. Namun perlu diingat, angka bukanlah segalanya.
Jika dibandingkan dengan jalur pendakian Gunung Semeru—yang adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa—jalur pendakian Gunung Merapi lebih sulit, menurut saya. Selain jalurnya yang terus menanjak, pemandangan yang monoton hingga pos kedua juga membuat saya bosan terkadang. Jalur pendakian Gunung Semeru lebih menyenangkan dengan pesona alam yang jauh lebih beragam.
Kami banyak berhenti di sepanjang jalur pendakian. Berat juga jalurnya. Kami luput membeli banyak cemilan sebagai hiburan pendakian. Tidak ada sumber air pula. Merapi, meru api, gunung api. Kata saya dalam hati. Kami harus menghemat persediaan air minum, yang artinya beban kami tak akan banyak berkurang selama menanjak.
Pukul empat sore, kami tiba di pos kedua. Jika melihat keterangan pada papan informasi, dibutuhkan sekitar satu jam lagi untuk tiba di Pasar Bubrah. Namun jika melihat realita, waktu tempuh pendakian kami selalu melebihi estimasi waktu yang tertera pada papan informasi.

“Di sini enak, banyak pohon buat nahan angin. Alasnya juga tanah”, saya berusaha meyakinkan teman-teman agar mau mendirikan tenda di sini, “di Pasar Bubrah alasnya batu loh, ngga ada pohon juga buat ngehalangin angin. Kedua teman saya nampak menimbang-nimbang
“Pertimbangan lainnya, kita besok tinggal lanjutin perjalanan ke Pasar Bubrah tanpa carrier. Lebih enteng,” saya semakin semangat meyakinkan. Berhasil. Sore itu kami menunda perjalanan.
Dengan sigap, kami bertiga berbagi tugas membangun kemah. Mi goreng dan telur dadar dengan sedikit irisan cabai rawit pun menutup hari pertama kami di Gunung Merapi.
Saya terbangun. Tangan ini mencoba meraba dalam tenda yang gelap, berusaha mencari arloji. Pukul sebelas malam kalau tidak salah.
Ternyata hujan belum juga berhenti turun sejak sebelum kami tidur. Saya mengintip ke luar tenda. Sudah ramai. Kami yang tiba mendirikan tenda pertama di pos kedua. Tidak menyangka malam ini sangat ramai. Kami pikir, seluruh pendaki akan berkemah di Pasar Bubrah. Mungkin karena hujan.
Pasar Bubrah adalah kawasan kesukaan para pendaki mendirikan kemah. Letaknya yang benar-benar berada di bawah kubah puncak gunung menawarkan keuntungan sendiri: mempersingkat pendakian dari tenda ke puncak. Pasar Bubrah juga menjadi titik temu jalur pendakian Selo dan Sapuangin.
Mengapa disebut pasar? Apa dulu pernah ada pasar di sini? Tidak. Kabar burung menyebut beberapa pendaki kerap mendengar suara riuh pada malam hari, ramai seperti di pasar. Ada yang menyangkutpautkan suara riuh ini dengan aktivitas makhluk-makhluk gaib. Kawasan ini lantas disebut pasar bagi makhluk-makhluk gaib.
Beberapa tulisan yang saya temui di internet mencoba menjawab secara ilmiah. Suara riuh yang sering diakui didengar oleh beberapa pendaki adalah suara yang dihasilkan oleh pertemuan arus-arus angin yang datang dari berbagai penjuru. Maklum, Pasar Bubrah adalah tanah terbuka. Seperti padang bebatuan vulkanis.
Suara gemuruh—yang mungkin sama—sebenarnya juga terdengar dari pos dua ketika hujan turun pada malam hari. Jelas sekali itu adalah suara angin. Memang benar, suaranya keras sekali. Agak menyeramkan.
Jadi bukan suara riuh seperti manusia? Ada juga riuh suara manusia, tentu. Sampai menjelang tengah malam, penghuni beberapa tenda yang ada di sekitar kami berisik sekali. Saya seketika seperti mendapat penjelasan dari mitos suara riuh di Gunung Merapi.
Namun, apakah Pasar Bubrah seramai itu? Iya! Keesokan paginya, saya tiba di Pasar Bubrah saat menuju puncak. Hari Minggu, memang. Wajar jika Merapi, khususnya Pasar Bubrah, seramai itu.

Dari kejauhan, warna-warni tenda begitu jelas terlihat. Kontras sekali dengan panorama Pasar Bubrah yang monokromatis. Monokromatis sekaligus misterius. Kabut putih tebal sesekali meluncur menyergap kami yang sedang berada di Pasar Bubrah. Tak ada pohon di sini seingat saya. Saya bisa membayangkan betapa dinginnya angin malam di sini.
Sebenarnya, Pasar Bubrah adalah batas pendakian bagi kami. Jelas-jelas ada papan peringatan yang ditanam di dekat puncak untuk menangkal para pendaki menuju puncak.
“Bukan tanpa alasan. Merapi adalah gunung berapi aktif. Bebatuan di kubah lava selalu terbentuk, sehingga batu yang dipijak pendaki adalah bebatuan labil. Bisa longsor atau gugur kapan saja. Belum lagi ada potensi lemparan batu dari dalam kawah. Ini bukan saran, ini larangan”, salah seorang petugas Taman Nasional Gunung Merapi yang saya temui di Jakarta memberi penjelasan.
Namun saya, bersama puluhan pendaki lainnya saat itu, adalah para pendaki bebal. Tak acuh pada peraturan. Kami mendaki hingga puncak. Tertatih, terseok, lalu terperosok setiap melangkah di medan bebatuan yang memang rapuh.

Jalur menuju puncak Merapi mirip dengan jalur menuju puncak Semeru atau Rinjani, namun tidak sejauh Semeru saya rasa. Awalnya, saya beberapa kali terperosok karena medan yang saya pijak adalah kerikil dan bebatuan kecil. Namun semakin jauh, medan perjalanan didominasi oleh bebatuan yang lebih besar dan lebih mudah dipijak.
Puncak Merapi adalah bibir kawah yang menganga. Jalurnya sempit. Tak jarang pendaki yang mondar-mandir di puncak harus saling menunggu, bergiliran melintas.
Dari atas, jelas sekali terlihat kawah Merapi. Asap dari dasar kawah membumbung ke langit. Beberapa pendaki saya lihat berani betul mendekat ke bibir kawah untuk berfoto. Saya tidak berani.

Sementara, dua teman saya ternyata berhenti di tengah perjalanan menuju puncak dan kembali ke kemah. Kondisi fisik salah satu dari mereka tidak memungkinkan melanjutkan pendakian, apalagi untuk meneruskan perjalanan ke Gunung Merbabu.
Akhirnya, kami tiba kembali di pintu masuk pendakian di New Selo menjelang sore. Rencana ke Merbabu harus ditunda. Kami pun menutup perjalanan dengan menyewa sebuah pondok di kaki Merapi. Pondok terbaik di sana, saya pikir. Pondok dengan pemandangan langsung ke Gunung Merapi dari dalam kamar. Merbabu, kami akan datang suatu hari.

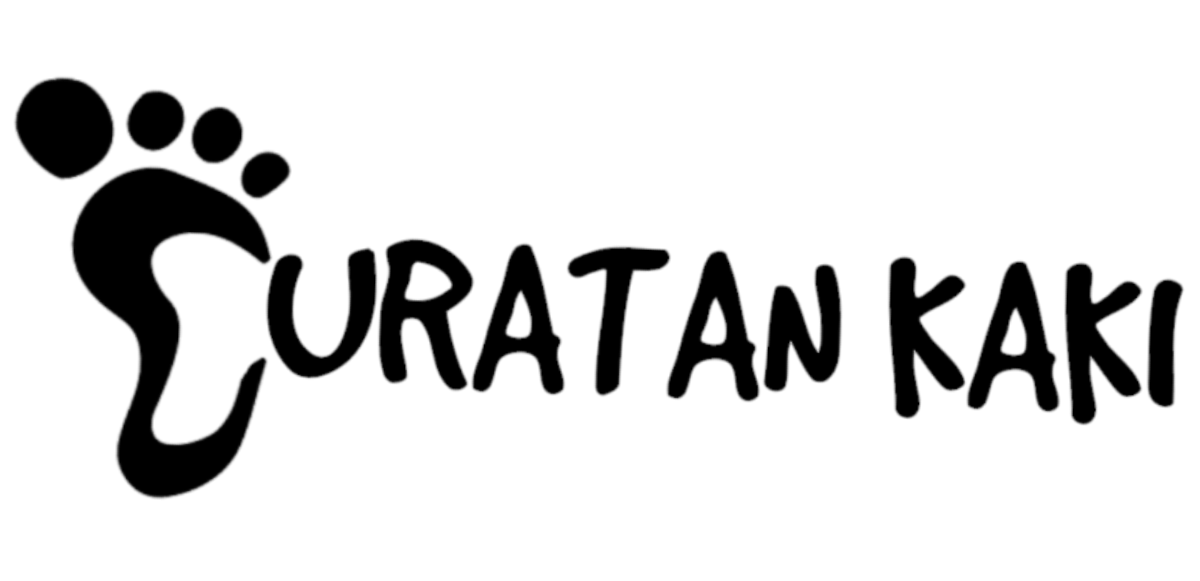

Merapi sekarang ada porternya gak mas, Agak males sekarang bawa2 tas gede kayak dulu. hahahaha
LikeLike
Waduh, saya ngga ngeh waktu itu ada porternya atau ngga. Ngga merasa lihat dan ngga ada yang nawarin sih, Mas 😅 Harusnya ada ya. Hehe.
LikeLike
Hahahaha siaap mas, nanti aku cari info lagi 😀
LikeLike
Hehe oke, Mas.. Kalau mau, saya ada kontak driver yang kemarin jemput saya di Solo. Dia warga Selo, rumahnya juga jadi tempat singgah tamu pendaki untuk mandi dsb. Seharusnya dia punya info/bisa bantu sambungkan ke porter 😃
LikeLiked by 1 person
Siaaap mas, mauuuuuuu
LikeLike
Namanya Mas Parno, 0857-0153-0649. Bilang aja dikasih tau sama saya hehe.
LikeLike
Siap mas, terima kasih banyak. Sukses selalu yaaa mas 🙂
LikeLiked by 1 person
Dengan senang hati, Mas. Kalau Merapi belum dibuka, Mas Parno juga bisa bantu untuk ke Merbabu. Hehe. Sukses juga!
LikeLiked by 1 person
Siap mas, lagi pengen naik gunung nih.. udah rindu. hehehehe
LikeLike
Iya, Mas. Gunung selalu berhasil “detoks” penat kehidupan 😂 *lah curhat
LikeLike